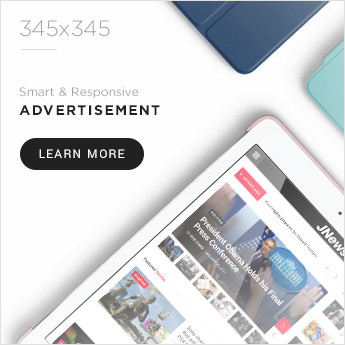Jakarta, innews.co.id – Tren kriminalisasi terhadap profesional yang tulus membangun BUMN menjadi sinyal buruk bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut akan menimbulkan ketakutan sistemik di kalangan sumber daya manusia terbaik untuk mengabdi pada bangsa dan negara.
Hal tersebut dikatakan pakar psikologi komunikasi Dr. Geofakta Razali. “Saat ini muncul kekhawatiran bahwa sejumlah kasus hukum dipersepsikan publik sebagai upaya pencarian kambing hitam. Pada akhirnya ini bisa membuat individu terbaik takut mengambil keputusan bisnis,” kata Geofakta, di Jakarta, Minggu (8/2/2026).
Menurutnya, ada kecenderungan sistemik untuk mengkriminalisasi risiko bisnis demi memenuhi ekspektasi moral publik akan “kambing hitam”.
Dalam psikologi organisasi, kata dia, hal ini dikenal sebagai scapegoating bias, kebutuhan kolektif untuk menunjuk figur simbolik ketika sistem mengalami kegagalan.
Dicontohkan kasus berlatar motif mencari kambing hitam antara lain, mulai dari Dirut PT Pelindo II (Persero) RJ Lino, Dirut PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, hingga komisaris PT Indofarma Global Medika (IGM)–anak usaha PT Indofarma, Arief Pramuhanto.
“Mereka itu orang cerdas yang bekerja secara profesional untuk memajukan BUMN,” ujarnya.
Seperti diketahui, meski tak terbukti menerima aliran dana, tak memiliki kewenangan operasional, dan secara formil telah menjalankan fungsi pengawasan, Arief tetap divonis bersalah.
Dia menilai kasus Arief dan beberapa kasus serupa dapat dipandang sebagai anomali hukum yang mengusik rasa keadilan, di mana seorang profesional ditarik ke pusaran pidana bukan dalam kepasitasnya sebagai direksi yang melakukan eksekusi harian, melainkan murni dalam kapasitasnya sebagai komisaris di sebuah anak usaha BUMN.
“Di level permukaan, menjerat komisaris ke ranah pidana terlihat sebagai bentuk kehati-hatian hukum. Namun jika dibaca mendalam, anomali ini mengungkap problem komunikasi institusional yang serius,” urainya.
Diingatkan, komisaris itu secara struktural bukanlah pengelola operasional. Secara normatif, perannya dibatasi oleh regulasi dan prinsip tata kelola perusahaan. Intinya, komisaris hanya mengawasi dan memberi nasihat.
Dikatakannya, bias sistemik membuat publik terjebak dalam bingkai seolah Arief sebagai dirut di BUMN dan menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas perkara yang terjadi di anak usaha BUMN tersebut.
Repotnya, sambung dia, logika hukum itu runtuh oleh satu asumsi psikologis yang berbahaya kalau terjadi kerugian, pasti ada yang lalai. Kalau ada yang lalai, harus ada yang dihukum.
“Ini adalah bentuk outcome bias, yakni menilai benar-salah keputusan bukan dari proses dan niatnya, tetapi pada hasil akhirnya,” tukasnya.
Dunia bisnis modern mengenal Business Judgment Rule (BJR) yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip yang justru dibangun untuk melindungi pengambil keputusan dari kriminalisasi risiko. Selama keputusan diambil dengan itikad baik, berbasis informasi memadai, tanpa konflik kepentingan, dan untuk kepentingan perusahaan, maka kerugian yang muncul adalah risiko bisnis, bukan kejahatan.
“Secara psikologis, BJR penting bukan hanya sebagai doktrin hukum, tetapi sebagai mekanisme keamanan psikologis dalam organisasi. Tanpa perlindungan ini, setiap aktor strategis akan bermain aman, menghindari inovasi dan akhirnya justru membunuh daya saing BUMN,” terangnya.
Diingatkan, tanpa kepastian hukum yang adil dan konsisten, rasa aman psikologis para profesional akan tergerus. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan agenda reformasi dan transformasi BUMN di era pemerintahan Presiden Prabowo
Karenanya, bila tidak segera merespon tren kriminalisasi terhadap para profesional ini, risiko kerugian bagi Pemerintahan Prabowo akan membayangi. (RN)