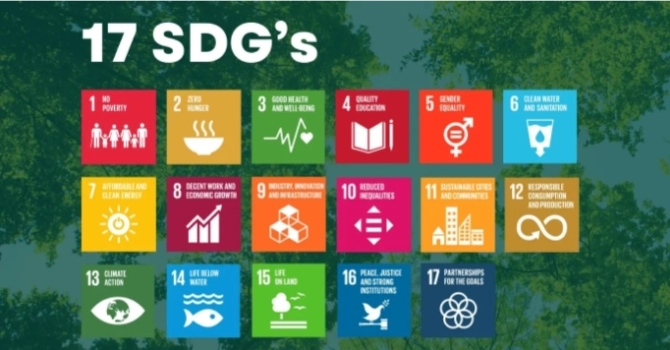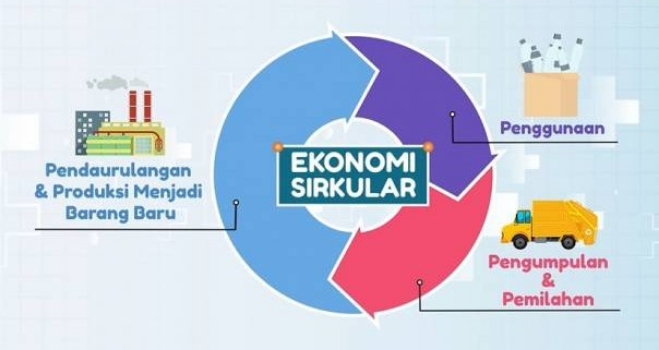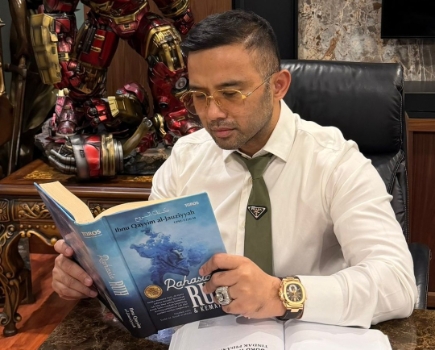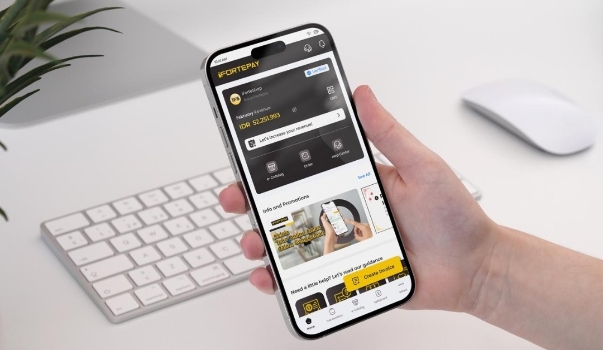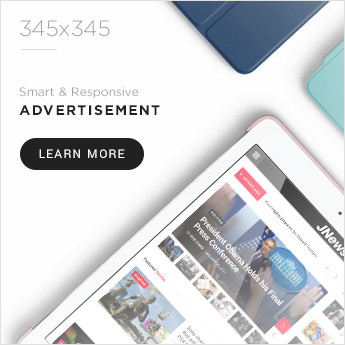Jakarta, innews.co.id – Program hilirisasi sektor perkebunan ditengarai justru menyuburkan masuknya korporasi asing. Pasalnya, dalam implementasi, program tersebut masih sangat bergantung pada modal dan keahlian asing. Hal tersebut kentara pada komoditi sederhana, seperti kelapa.
Pada Juli–Agustus 2025, pemerintah memberi karpet merah terhadap perusahaan Tiongkok, yang berinvestasi sekitar US$100 juta (Rp 1,6 triliun) untuk membangun pabrik pengolahan turunan kelapa di beberapa daerah.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa Indonesia selama ini hanya mengekspor kelapa mentah. Padahal bila diolah di dalam negeri dapat melipatgandakan nilai. Bahkan pemerintah menyebut potensi nilai hilirisasi Rp 400-2.600 triliun. Namun, pemicunya justru investor asing.
“Ini menunjukkan bahwa ekosistem lokal belum siap menangkap peluang yang sebenarnya bukan “rocket science,” kata mantan Anggota Komisi IV DPR RI, Capt. Dr. Anthon Sihombing, MM., M.Mar., dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Dia menegaskan, ekspor perdana 81 ton produk turunan kelapa dari Kepri ke Tiongkok membuktikan bahwa pasarnya ada. Pertanyaannya, mengapa skala dan koordinasinya baru berjalan setelah pihak asing turun tangan?
Kelemahan
Baginya, program hilirisasi sepertinya justru membuka tabir ketidakmampuan Indonesia dalam membuat produk turunan hasil perkebunan.
“Harusnya program hilirisasi dapat memperkuat bisnis lokal, bukan asing,” ujar Dewan Etik DPP Golkar ini.
Kelemahan yang nampak, lanjut Anton, antara lain, dukungan research and development (R&D) yang minim, institusi pendukung usaha yang belum efektif menarik inovasi ke pasar, dan kebijakan industri yang cenderung reaktif, yaitu merayakan masuknya pabrik asing, bukan memperkuat inovator lokal.
Menurutnya, rendahnya belanja riset pemerintah (hanya sekitar 0,06% PDB di 2022), membuat peringkat R&D Indonesia oleh Bank Dunia ditempatkan pada posisi rendah.
“Ada kecenderungan inovasi sulit dihilirkan ke pasar global. Global Innovation Index 2024 menempatkan Indonesia di peringkat 54, dengan output inovasi (67) lebih lemah dibanding input (54). Itu artinya, komersialisasi pengetahuan belum berjalan optimal. Bahkan tidak ada satu pun klaster sains-teknologi Indonesia yang masuk Top-100 dunia,” terang Senior SOKSI ini.
Tak hanya itu, laporan B-Ready 2024 menyoroti kelemahan Indonesia seperti persaingan pasar, layanan keuangan, dan rezim kepailitan, termasuk ketiadaan TTO (kantor alih teknologi), serta science & technology parks, yang krusial untuk mendukung UKM pengolah.
“Riset dan pengembangan yang kurang dan terpusat, membuat UKM kekurangan inovasi proses, kemasan, dan pemenuhan standar,” jelas politisi senior Partai Golkar ini.
Demikian juga infrastruktur hilirisasi inovasi, pembiayaan berisiko, dan mekanisme restrukturisasi UKM yang memadai masih belum tersedia. Bahkan, insentif kebijakan lebih fokus pada pabrik FDI ketimbang melahirkan produsen peralatan, koperasi pengolah, dan pemilik merek lokal. Akibatnya, rente koordinasi dan pengetahuan proses dinikmati pihak asing.
Realitis dan terukur
Ketua Umum International Maritime Organization (IMO) Watch ini menyarankan agar pemerintah, pertama, menaikkan anggaran R&D publik berbasis misi (proses, keamanan pangan, pengemasan, pemanfaatan limbah) dengan skema co-funding bagi UKM/koperasi. Adapun target kenaikan bertahap hingga minimal 0,3% dari PDB.
Kedua, membangun TTO & techno-park di sentra kelapa dengan fasilitas laboratorium bersama (pengeringan, fraksinasi, uji mutu) dan jalur produksi percontohan guna menutup ‘kesenjangan institusional’, seperti yang disorot B-Ready.
Ketiga, tarik pasar lewat percepatan standar dan belanja publik. Misalnya, percepat SNI/halal/HACCP dengan sistem voucher; gunakan pengadaan pemerintah (misalnya program gizi sekolah) untuk mendorong penggunaan produk kelapa lokal—mengatasi kelemahan ‘output’ di GII.
Keempat, menyediakan pembiayaan untuk ‘missing middle’: dana penyangga risiko, pembiayaan piutang, dan KUR khusus modernisasi alat; sederhanakan aturan kepailitan agar lebih ramah UKM.
Kelima, pastikan FDI membawa transfer keahlian: wajibkan porsi produksi alat lokal, program pengembangan pemasok, dan ko-kreasi pengetahuan proses dengan lembaga riset Indonesia; dorong joint-venture (JV) yang benar-benar mentransfer teknologi, bukan hanya impor lini produksi jadi.
Anton menyimpulkan, masalah utama Indonesia bukan kurangnya visi, melainkan kurangnya kapasitas negara membangun ekosistem inovasi.
“Tanpa peningkatan signifikan di R&D publik, infrastruktur pendukung dan pembiayaan, investor asing akan terus ‘mengorganisir’ hilirisasi. Sementara margin, pekerjaan berkualitas, dan keahlian teknologi & proses produksi malah ikut terserap ke luar negeri,” pungkasnya. (RN)